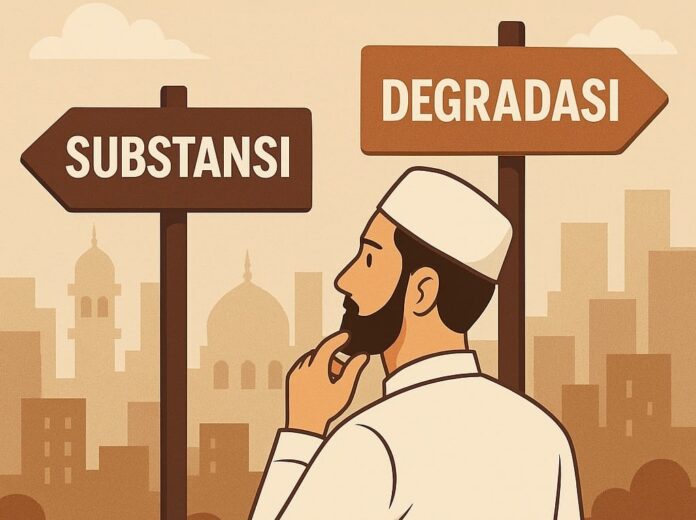Oleh Rahman Saleh | Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PDM Jakarta Selatan
PRAGMATISME adalah aliran filsafat yang memandang kebenaran berdasarkan manfaat yang dihasilkan. Sesuatu dianggap benar sejauh memberikan kegunaan bagi tindakan manusia dalam menjalani hidup. Istilah “pragmatisme” berasal dari bahasa Yunani pragma, yang bermakna fakta, benda, kegiatan, tindakan, atau hasil pekerjaan. Dari berbagai arti tersebut, pragmatisme dipahami sebagai cara berpikir yang menekankan fungsi gagasan dalam tindakan nyata.
Sebagai logika berbasis pengamatan, pragmatisme menganggap dunia sebagai kumpulan fakta-fakta yang nyata, terpisah, dan bersifat individual. Kenyataan ditampilkan sebagaimana adanya; setiap pengalaman bersifat pribadi dan tidak bisa digeneralisasi. Dalam pandangan ini, suatu gagasan dianggap sah jika ia berguna atau berhasil dalam praktik. Itulah sebabnya, pragmatisme mengabaikan perdebatan filosofis tentang nilai-nilai kebenaran abstrak, termasuk yang bersifat keagamaan atau metafisik.
Dalam konteks kehidupan berbangsa, pragmatisme tampak menonjol dalam praktik politik Indonesia yang sarat dengan keragaman dan tuntutan kohesi sosial. Salah satu contoh nyata adalah perubahan frasa dalam Piagam Jakarta: dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Meskipun sebagian kalangan muslim merasa kehilangan secara simbolik, namun kompromi tersebut memperkokoh fondasi Proklamasi Kemerdekaan dan menjaga keutuhan bangsa. Kalangan nonmuslim tetap merasa menjadi bagian dari Republik yang inklusif.
Namun pragmatisme juga telah menggeser orientasi politik dari yang bersifat ideologis ke arah yang lebih praktis. Dalam era kontemporer, partai-partai Islam cenderung menyamarkan identitas ideologis mereka. Beberapa mengadopsi asas Pancasila secara formal dan menyesuaikan platformnya dengan konstitusi UUD 1945. Penyesuaian ini bisa dibaca sebagai warisan ideologisasi era Orde Baru, semacam trauma kolektif sebagaimana bangsa Israel yang pernah menuntut Tuhan hadir dalam bentuk patung sapi emas karena terbiasa hidup dalam rezim pagan Mesir.
Kecenderungan pragmatis ini juga berkaitan dengan perubahan geopolitik global pascareformasi. Kampanye global Amerika Serikat tentang “perang terhadap terorisme” (War on Terror) memunculkan stereotipe negatif terhadap identitas keislaman dalam organisasi politik. Konsep teror yang dimaknai secara materiil, bukan formil, membuat ruang tafsir terhadap ideologi menjadi sangat lentur dan rawan dimanipulasi. Bahkan dalam pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas), muncul wacana memasukkan “ideologi terlarang” sebagai ancaman negara—sebuah konstruksi yang bisa menjustifikasi tindakan represif terhadap ide-ide yang dianggap menyimpang dari arus utama.
Dalam situasi demikian, bukan hanya publik, tetapi juga para elite politik Islam mengambil langkah-langkah taktis. Mereka memilih nama partai yang tidak langsung terasosiasi dengan Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sebagian memulai dengan asas Islam dalam AD/ART-nya, namun kemudian mengubahnya menjadi Pancasila setelah mempertimbangkan hasil pemilu.
Faktor lainnya adalah realitas elektoral yang sangat kompetitif dan menguras sumber daya. Dalam Pemilu 1999, kekuatan politik Islam tidak tampil sebagai pemenang. PDIP dan Golkar yang berhaluan nasionalis berhasil menguasai lebih dari separuh suara (masing-masing 33,12% dan 25,97%). Partai-partai baru yang lahir dari faksi Golkar dan ABRI, seperti Gerindra, Demokrat, dan NasDem, kemudian berhasil menembus parlemen hingga 2024.
Realitas pemilu turut membentuk kesadaran baru bahwa identitas Islam dalam politik bisa menjadi hambatan elektoral. Ide-ide tentang Islam sebagai sistem pemerintahan tidak berkembang luas karena perdebatan publik lebih didominasi oleh isu-isu praktis seperti ekonomi makro dan mikro. Dalam membedah APBN dan APBD, pendekatan ilmu ekonomi dianggap lebih relevan. Sementara itu, sistem hukum Indonesia lebih condong ke tradisi hukum kontinental Eropa, warisan Napoleon. Meski demikian, beberapa aspek hukum Islam tetap hadir dalam sistem politik dan ekonomi, seperti kewenangan Peradilan Agama (soal perkawinan, perceraian, dan warisan), Baznas (zakat), BWI (wakaf), serta lembaga-lembaga pengelola haji seperti Kementerian Agama, BPH, dan BPKH.
Wacana fikih dan teologi Islam kini lebih berkembang di dunia akademik dan forum-forum nonformal seperti majelis taklim dan pengkaderan organisasi massa Islam. Islam sebagai agama yang dianut oleh 87,06% penduduk Indonesia perlu terus ditanamkan secara mendalam di tingkat akar rumput: diajarkan, dipahami sebagai nilai, lalu diadopsi sebagai pandangan hidup.
Tulisan ini mencoba membaca adanya disparitas antara keyakinan keislaman masyarakat dengan pilihan politiknya. Ini tercermin dalam lemahnya dukungan terhadap partai-partai Islam. Para elite politik pun, dengan pertimbangan rasional, akan terus beradaptasi untuk memperoleh dukungan publik. Dalam kerangka ini, pragmatisme yang muncul bukan niscaya sebuah keburukan. Ia bisa menjadi langkah transisional sembari terus dilakukan upaya peningkatan kesadaran politik Islam di tengah masyarakat. Islam yang substansial tidak harus tampil dengan simbol-simbol formal, melainkan melalui pemahaman yang mendalam, inklusif, dan menjawab kebutuhan zaman. (*)