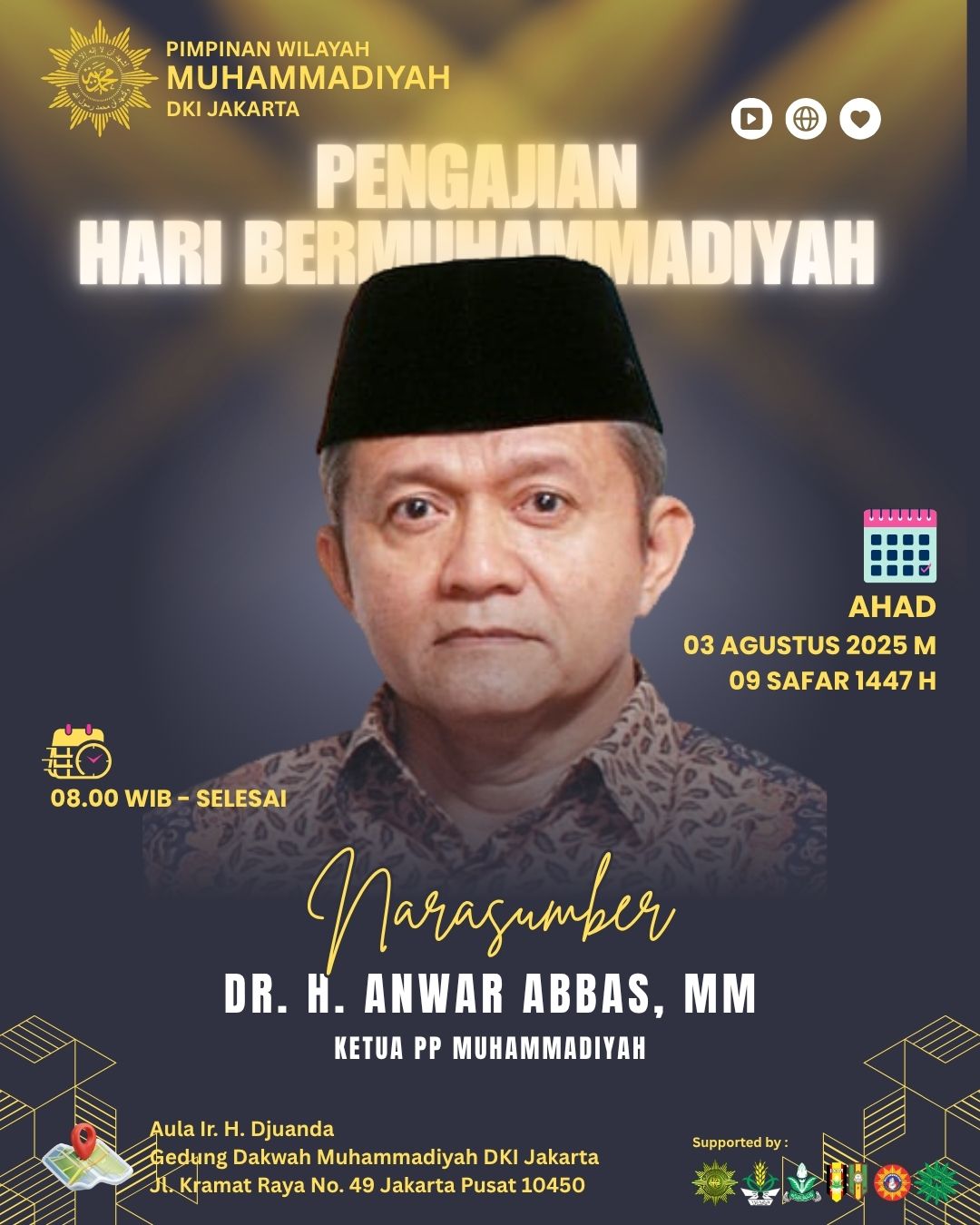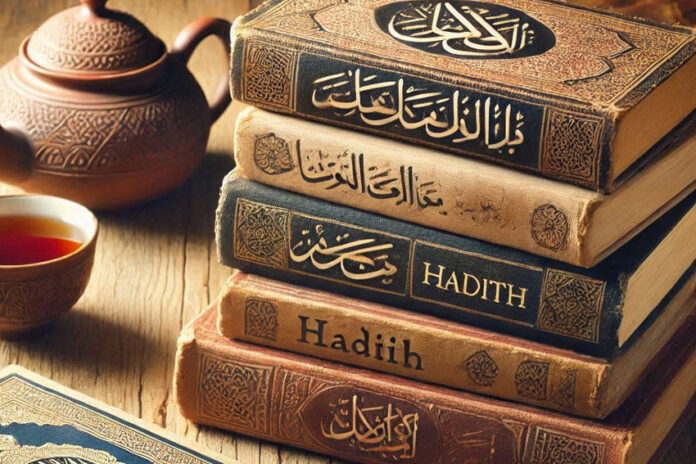JAKARTAMU.COM | Nobelis bidang kedokteran, Dr. Alexis Carrel, pernah mengeluhkan ketakmampuan sains memahami manusia secara utuh. “Kita hanya mengetahui beberapa segi tertentu dari diri kita,” tulis Carrel dalam Man the Unknown. Dalam pandangannya, manusia yang sudah berabad-abad hidup dengan dirinya sendiri, masih menjadi teka-teki paling pelik dalam jagat pengetahuan.
Keluhan Carrel, meski datang dari dunia laboratorium, sejalan dengan ayat Al-Qur’an yang menjawab tanya para sahabat Nabi soal roh. “Katakanlah: Roh itu urusan Tuhan-ku, dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit,” (QS Al-Isra’: 85).
Dua kutipan ini seolah berpaut pada benang merah yang sama: ada batas yang tak bisa ditembus oleh ilmu pengetahuan modern, betapapun canggih perangkatnya. Sains mampu membedah jantung dan memetakan genom, tapi tetap gamang soal roh, akal, dan kesadaran. Maka, bila sains tak cukup, wahyu tampil sebagai alternatif epistemologis yang tak bisa dikesampingkan.
Tiga Masalah Utama: Mengapa Kita Tak Paham Diri Sendiri?
Dalam kerangka ini, Carrel merumuskan tiga sebab utama kegagalan manusia memahami dirinya sendiri.
Pertama, keterlambatan perhatian ilmu terhadap manusia. Sejak zaman purba hingga modern, orientasi utama manusia adalah menaklukkan alam dan mengendalikan materi. Akibatnya, pemahaman terhadap jiwa tertinggal jauh di belakang teknologi.
Kedua, keterbatasan akal manusia itu sendiri. Filsuf Prancis Henri Bergson menilai bahwa akal manusia cenderung berpikir secara linier dan mekanistik. Ia sulit menangkap dimensi spiritual yang non-materiil dan transenden.
Ketiga, kompleksitas manusia sebagai entitas multidimensi. Manusia adalah perpaduan tubuh, jiwa, akal, emosi, sejarah, lingkungan, dan budaya. Semua berkelindan dalam satu paket yang tak mudah dirumuskan secara tunggal.
Tiga sebab itu membuat sains modern, menurut Carrel, hanya mampu menjamah kulit luar manusia. Tak heran jika dalam dunia keagamaan, banyak yang mulai kembali mengusulkan pentingnya pendekatan wahyu dalam memahami manusia. Tapi pendekatan ini tak boleh serampangan. Harus sistemik, menyeluruh, dan tematik. Di sinilah metode tafsir maudhu’i menjadi penting: membedah makna manusia dengan merujuk seluruh ayat Al-Qur’an yang relevan secara tematik dan kontekstual.
Basyar dan Insan: Dua Nama, Dua Dimensi
Al-Qur’an sendiri menggunakan sejumlah istilah untuk menunjuk manusia. Tapi dua istilah utama yang sering muncul adalah basyar dan insan. Masing-masing bukan sinonim, melainkan penanda dimensi yang berbeda.
Kata basyar berasal dari akar kata basyarah, yang berarti kulit atau permukaan tubuh. Dalam Tafsir al-Kabir, Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa basyar menunjuk pada sisi biologis dan lahiriah manusia. Ia tumbuh, makan, tidur, berkembang biak, dan menjalani kehidupan ragawi.
Nabi Muhammad pun dalam Al-Qur’an digambarkan sebagai basyar: “Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang basyar seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku…” (QS Al-Kahfi: 110). Ini mempertegas bahwa basyar bukan istilah peyoratif, tapi deskriptif: ia merujuk pada dimensi fisik, sosial, dan instingtual manusia.
Sementara itu, istilah insan membawa nuansa yang lebih dalam. Dalam Wawasan Al-Qur’an, Prof. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa insan menunjuk pada manusia sebagai makhluk sadar—makhluk yang memiliki kehendak, tanggung jawab, dan kesadaran moral. Dalam kata ini terkandung kelemahan sekaligus potensi luhur manusia: ia bisa lupa, tapi juga bisa taubat; bisa dzalim, tapi juga bisa adil.
Ayat-ayat seperti QS Al-‘Alaq: 2 (“Dia menciptakan insan dari segumpal darah”) dan QS Al-Insan: 1 (“Bukankah telah datang kepada insan satu waktu…”) menjadi penanda bahwa insan adalah subjek sejarah dan moral, bukan sekadar makhluk biologis.
Gabungan Ilmu dan Wahyu
Kombinasi antara basyar dan insan memberikan pemahaman yang lebih integral tentang manusia. Ia bukan hanya tubuh yang bergerak, tapi juga ruh yang mencari. Ia bukan sekadar entitas biologis, tapi juga aktor moral dan spiritual. Maka, menurut Quraish Shihab, memahami manusia tanpa wahyu seperti membaca buku tebal tanpa lampu: teksnya mungkin lengkap, tapi tetap gelap.
Pernyataan itu sejalan dengan kesimpulan Carrel: sains belum mengenal manusia secara utuh. Meski sains bisa mengungkap fungsi otak, ia tak mampu menjelaskan kesadaran. Meski psikologi memetakan emosi, ia tak bisa mengurai makna cinta atau keikhlasan. Bahkan kecerdasan buatan—yang makin menyerupai perilaku manusia—tetap kehilangan satu unsur krusial: jiwa.
Maka, di tengah kekosongan pengetahuan modern soal ruh, wahyu hadir bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai penerang. Ia bukan pengganti sains, tapi jembatan menuju pemahaman yang lebih utuh. Sebab, manusia bukan hanya basyar yang berpijak di bumi, tapi juga insan yang menengadah ke langit. (*)