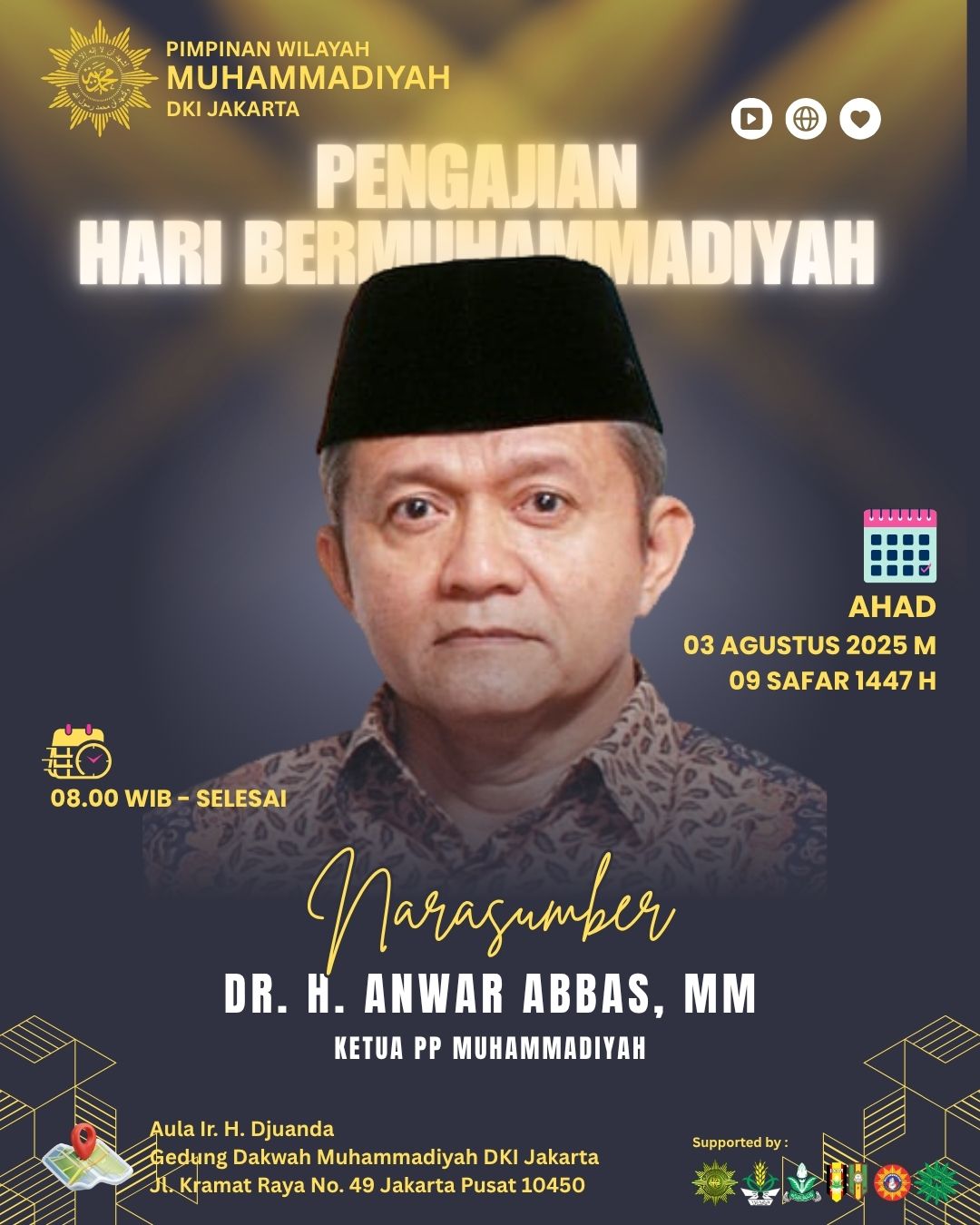JAKARTAMU.COM | Di balik dinding fakultas-fakultas usuluddin, suasana akademik seolah tak pernah surut. Mahasiswa sibuk membolak-balik kitab klasik tebal berbahasa Arab, menelaah al-Mawaqif karya Adududdin al-Iji, lengkap dengan syarah al-Jurjani yang rumit. Tema besar yang dibahas bukanlah ekonomi syariah atau tantangan etika digital, melainkan persoalan metafisika ala Aristoteles: al-muqaddimat, al-thabi’iyyat, dan silsilah wujud yang abstrak.
Namun pertanyaan menggantung: seberapa banyak dari energi intelektual itu yang akan bermuara pada problem keumatan hari ini?
Dalam Fiqh al-Awlawiyyat atau Fiqh Prioritas, Syaikh Yusuf al-Qardhawi mengetuk pintu kesadaran umat: “Banyak pelajaran yang menghabiskan tenaga dan waktu para pelajar, padahal separuh atau seperempat dari waktu itu dapat dipakai untuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagi agama dan dunia mereka.”
Seruannya lahir dari kegelisahan terhadap cara umat Islam mengelola keilmuan. Warisan klasik terus diwariskan tanpa filter zaman. Di banyak pesantren dan kampus keislaman, mahasiswa didorong menghafal rumusan debat lama tanpa ruang untuk mempertanyakan relevansi dan prioritasnya.
Qardhawi bukan anti-tradisi. Ia tidak menyerukan pemutusan dengan warisan ulama. Ia hanya menggugat penempatan yang keliru—antara ilmu yang mesti didahulukan dan yang bisa dikesampingkan. Ilmu agama, katanya, seperti makanan: bukan banyaknya yang penting, melainkan gizi dan manfaatnya.
Warisan atau Beban?
Kegelisahan Qardhawi menemukan konteksnya dalam sistem pendidikan Islam yang masih berkutat pada teks klasik sebagai fondasi utama. Di ruang-ruang kelas, diskusi teologis kerap tak menyentuh dunia nyata. Mahasiswa lebih fasih menjelaskan kontradiksi antara Imam Asy’ari dan Mu’tazilah ketimbang membaca peta problematika urbanisasi atau perubahan budaya masyarakat Muslim digital.
Ilmu kalam masih disampaikan dengan pendekatan logika Yunani, yang bahkan oleh sebagian dosen dirasa membingungkan. Padahal, kata Qardhawi, era ini membutuhkan pendekatan yang menjangkau kesadaran modern: yang berbicara dengan data, observasi, dan empati. Ia mengutip Ibn al-Wazir, ulama Yaman abad pertengahan, yang menulis Tarjih Asalib al-Qur’an ‘ala Asalib al-Yunan—kitab yang menolak dominasi filsafat Yunani dalam menjelaskan akidah.
Jika metode Aristoteles tak lagi relevan, mengapa masih menjadi menu utama pendidikan akidah?
Fikih yang Tak Menyapa Zaman
Tak hanya ilmu kalam, bidang fikih pun menjadi sorotan. Qardhawi mencermati bagaimana diskursus keislaman masih didominasi soal najis, haid, dan khilafiyah yang berputar di tempat. Padahal, dunia tengah menghadapi isu besar: perbankan syariah, ekonomi digital, krisis iklim, bahkan rekayasa genetika.
“Fikih itu ibarat kompas,” tulis Qardhawi, “ia harus bisa menunjukkan arah dalam perubahan.”
Namun alih-alih menjadi kompas, fikih kini kerap menjadi beban. Debat panjang soal apakah Nabi Muhammad adalah makhluk pertama, atau bagaimana hukum memakai cincin di tangan kanan, menyedot energi umat tanpa kontribusi terhadap pembangunan sosial.
Kita lupa bahwa prioritas dalam beragama tak hanya antara halal dan haram, tapi juga antara maslahat dan mafsadat, antara yang mendesak dan yang bisa ditunda.
Dakwah Buta Konteks
Problem ini juga menjalar ke dunia dakwah. Banyak juru dakwah hanya memindahkan isi kitab kuning ke mimbar atau media sosial. Topik-topik berat seperti filsafat Ibn Sina dibawakan ke hadapan buruh pabrik. Retorika dibangun dari kisah Israiliyat dan hadis lemah.
Qardhawi menyebut ini sebagai “krisis relevansi dakwah.” Pesan disampaikan tanpa memahami audiens. Ceramah dibangun tanpa peta kebutuhan umat.
Dakwah, menurutnya, harus bersifat kontekstual. Apa yang disampaikan kepada cendekiawan tidak boleh sama dengan yang disampaikan kepada nelayan. Penyuluh agama tidak cukup hanya hafal dalil, tapi mesti memiliki kepekaan sosial, wawasan lintas ilmu, dan kemampuan menjawab isu mutakhir.
Menyusun Ulang Kurikulum Islam
Seruan Qardhawi bukan sekadar kritik terhadap kurikulum, tapi seruan untuk menyusun ulang arah gerak peradaban Islam. Ia mengajak agar pendidikan agama tak hanya mencetak penghafal, tapi juga pemikir dan pelayan umat.
Ia merekomendasikan agar mahasiswa diberi akses pada karya seperti Allah wa al-‘Ilm al-Hadits (Allah dan Ilmu Modern) atau Al-‘Ilm Yad’u ila al-Iman (Ilmu Mengajak kepada Iman). Bukan karena modernisme lebih penting, tapi karena zaman menuntut keterkaitan antara iman dan realitas.
Qardhawi tidak sendiri. Banyak pemikir Islam kontemporer dari Fazlur Rahman, al-Attas, hingga Taha Jabir al-Alwani berbicara senada. Bahwa warisan itu penting, tapi harus dikemas ulang, dikontekstualisasikan, dan diberi ruh baru.
Sebuah Jalan Tengah
Di titik ini, Fiqh Prioritas menjadi tawaran jalan tengah. Ia tidak menafikan khazanah klasik, tapi mendorong agar ia dipilah, disaring, dan disesuaikan. Prioritas, bukan penghapusan. Reformasi, bukan revolusi.
Jika umat Islam ingin menjadi kekuatan global yang menjawab tantangan zaman, pendidikan agama tidak cukup hanya menghafal. Ia harus hidup, bergerak, dan menyentuh problem nyata.
Qardhawi menulis: “Tidak setiap yang penting itu mendesak, dan tidak setiap yang mendesak itu penting. Maka letakkanlah segala sesuatu pada tempatnya.”
Pesan itu, lebih dari sekadar nasihat. Ia adalah peta jalan.