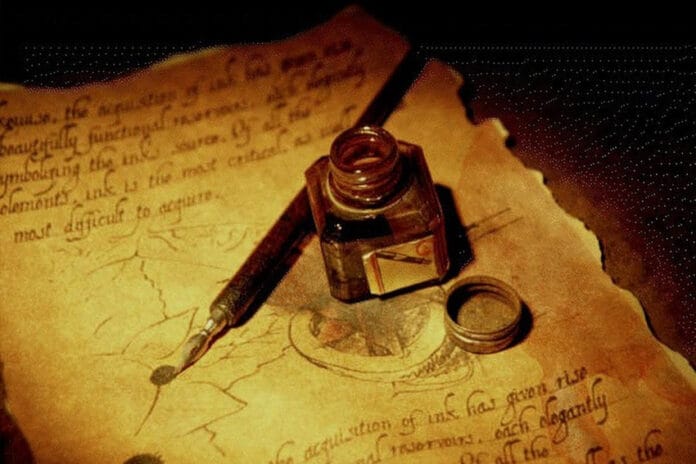JAKARTAMU.COM | Secara historis, pemikiran-pemikiran keagamaan (fikih atau teologi) yang ditawarkan oleh para pemikir Muslim sejak abad pertengahan lahir dari pola keprihatinan yang serupa, yakni bagaimana ajaran agama dapat dipahami umat secara benar. Ini merupakan bentuk keprihatinan teoretik yang melandasi munculnya pemikiran keagamaan.
KH Masdar F. Mas’udi dalam buku berjudul “Kontekstualisasi Doktrin Islam” bab “Telaah Kritis atas Teologi Muktazilah” (Yayasan Paramadina) mengatakan sebagaimana sering dikemukakan oleh para sejarawan, pada paruh kedua abad pertama Hijriah, terjadi dua perkembangan yang sangat signifikan dalam sejarah umat Islam.
Pertama, kenyataan bahwa di kalangan umat terjadi konflik internal yang kemungkinan besar tidak pernah diharapkan oleh mereka sendiri, di mana satu kelompok bukan hanya mengutuk kelompok lain, tetapi juga saling membunuh. Peristiwa tragis ini, yang terjadi dua kali, dikenal dengan sebutan fitnah kubra (cobaan besar).
Perkembangan kedua adalah masuknya bangsa Persia dan sekitarnya ke dalam Islam, beserta pemikiran dan keyakinan lamanya yang sudah tertanam kuat dalam benak mereka.
Dari dua perkembangan ini, muncul pertanyaan-pertanyaan teologis: Bagaimana hukum bagi orang Islam yang melakukan dosa besar (seperti membunuh sesama Muslim tanpa hak)? Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas tindakan manusia: dirinya sendiri atau kekuatan lain, dan dalam kendali siapa tindakan itu berada?
Menurut ajaran Islam, terdapat dua jenis balasan sejati di akhirat: balasan surga dan balasan neraka. Berkaitan dengan tanggung jawab manusia atas perbuatannya, faktor apa yang menentukan seseorang mendapatkan keselamatan dari Tuhan dan masuk surga? Apakah karena amal perbuatannya, ataukah semata-mata karena rahmat Tuhan yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya?
Pertanyaan ini sangat mungkin muncul karena, menurut doktrin Kristen yang pada saat itu sudah dikenal di kalangan umat Islam, “keselamatan Tuhan” tidak berkaitan dengan amal perbuatan manusia, melainkan semata-mata karena rahmat melalui satu jalan: Yesus.
Dari keprihatinan atas pertanyaan-pertanyaan inilah, para pemikir Islam pada masa itu merasa tertantang untuk merumuskan jawaban yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang sahih. Tentu saja, karena ajaran Islam pun harus diolah terlebih dahulu melalui subjektivitas masing-masing pemikir, maka jawaban yang muncul memiliki corak dan pendekatan yang berbeda-beda. Masing-masing jawaban kemudian berkembang menjadi aliran pemikiran yang berdiri sendiri.
Tersebutlah di kemudian hari nama-nama seperti Khawarij, Murji’ah, Mu’tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy’ariyah, Maturidiyah, Khasywiyah, dan sebagainya. Yang menarik adalah bahwa masing-masing aliran ini, karena merasa berpegang pada kebenaran mutlak, mengklaim sebagai satu-satunya yang benar dan menganggap yang lainnya salah.
Asal-Usul Mu’tazilah
Berbicara tentang awal mula sejarah Mu’tazilah, orang akan selalu merujuk pada episode diskusi Hasan al-Bashri (w. 110 H/728 M), seorang ulama terkemuka pada masanya, dengan murid-muridnya seputar tema Muslim yes, Muslim no. Pada masa itu, identitas seseorang sebagai bagian dari komunitas sangat ditekankan—apakah ia termasuk golongan “di dalam” (minna) atau “di luar” (minhum).
Terhadap pertanyaan yang muncul dalam diskusi Hasan tersebut, berkembanglah dua jawaban utama:
- Seorang Muslim yang melakukan dosa besar dianggap telah keluar dari komunitas (menjadi kafir) dan karena itu halal darahnya—pandangan ini dikemukakan oleh kelompok Khawarij.
- Seorang Muslim yang berdosa besar tetap tergolong Muslim, dan keputusan atas dosanya diserahkan kepada Tuhan di hari akhir—pandangan ini dianut oleh kelompok Murji’ah (berarti: menangguhkan).
Hasan al-Bashri sendiri, sebagai pemimpin yang ingin menjaga keutuhan umat, kemungkinan besar cenderung pada pandangan mayoritas ini. Maka, ketika Wasil bin Atha menyatakan pandangan yang berbeda, Hasan berkomentar dengan nada menyesal: Ia telah keluar dari kita—i’tazala ‘anna. Dari sinilah muncul istilah Mu’tazilah (yang mengasingkan diri), yang kemudian dilekatkan kepada Wasil dan para pengikutnya.
Teologi Kebebasan dan Keadilan
Jika pertanyaan mengenai status “pendosa besar” banyak dilatarbelakangi oleh motif politik, maka persoalan tentang kebebasan manusia lebih bersifat teologis murni. Di sinilah Mu’tazilah benar-benar berkembang sebagai aliran teologi tersendiri.
Berbeda dengan aliran lainnya, Mu’tazilah secara tegas menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan penuh untuk bertindak. Hanya dengan prinsip kebebasan inilah manusia dapat dimintai pertanggungjawaban secara moral di akhirat. Prinsip “janji dan ancaman” (al-wa‘d wa al-wa‘id) dalam kehidupan akhirat tidak dapat dipahami tanpa kebebasan manusia. Sebaliknya, prinsip kebebasan hanya berarti jika ada sistem balasan yang adil di akhirat.
Mu’tazilah meyakini bahwa balasan di akhirat sepenuhnya ditentukan oleh amal perbuatan manusia yang dilakukan secara bebas. Karena Tuhan Mahaadil, maka Dia harus membalas keburukan atas tindakan buruk dan membalas kebaikan atas tindakan yang baik. Sebagai Dzat yang Mahaadil, Tuhan tidak mungkin tidak bertindak adil kepada makhluk-Nya.
Agar manusia dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka ia harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk. Kemampuan ini, menurut Mu’tazilah, diberikan oleh Tuhan dalam bentuk akal—yang dipahami sebagai rasio atau nalar. Dengan nalarnya, manusia menjadi makhluk yang mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain dalam menentukan jalan hidupnya. Baik dan buruk (al-hasan wa al-qabh) tidak ditentukan dari luar, melainkan oleh nalar manusia itu sendiri.
Rasionalisme dan Kontroversi
Di titik inilah Mu’tazilah dikenal sebagai aliran pemikiran rasionalistik, yang mengedepankan otoritas akal (nalar) dibandingkan otoritas naql (wahyu). Pendirian ini dianggap membahayakan keutuhan doktrin oleh mayoritas umat Islam.
Namun apakah dengan demikian Mu’tazilah tidak lagi diperlukan? Tidak ada penegasan eksplisit mengenai hal ini. Akan tetapi, dengan tesis bahwa al-Qur’an adalah makhluk, Mu’tazilah telah menetapkan bahwa al-Qur’an (sebagai wahyu) tidak memiliki otoritas mutlak atas manusia, karena ia sama-sama makhluk.
Tesis tentang al-Qur’an sebagai makhluk berkaitan erat dengan prinsip “keesaan Tuhan” yang dibangun dengan pendekatan filosofis murni. Secara harfiah, prinsip ini bukanlah hal baru, namun yang membuatnya berbeda adalah pendekatannya yang menekankan tanzih—pembebasan Tuhan dari segala sifat, bahkan sifat-sifat yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur’an.
Menurut Mu’tazilah, sifat-sifat Tuhan tidak sebangun dengan hakikat-Nya. Jika hakikat Tuhan itu qadim (abadi), maka segala sesuatu selain-Nya, termasuk sifat-sifat-Nya, adalah hadits (diciptakan). Maka dari itu, al-Qur’an sebagai ekspresi dari salah satu sifat Tuhan (al-kalam) pun dianggap sebagai makhluk.