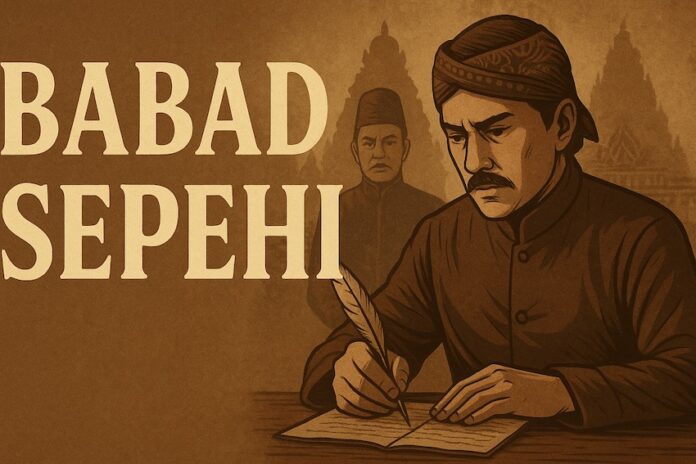FAJAR belum sempurna merekah ketika suara sorak tentara Sepehi dan dentang kemenangan terdengar dari arah Bangsal Pagelaran. Udara masih bau abu dan mayat. Namun di antara reruntuhan dan kepedihan yang mengendap, satu prosesi dijalankan dengan tergesa. Sultan Raja, yang kelak bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana III, berdiri di hadapan Crawfurd dan perwira Inggris lain, menerima serat pengangkatan sebagai penguasa baru Ngayogyakarta Hadiningrat. Upacara dilakukan tanpa sakralitas. Tak ada tarian Bedhaya Ketawang, tak ada para pujangga kraton membacakan tembang Jawa.
Yang hadir hanyalah suara merpati yang terganggu, dan bayang-bayang panjang dari tombak-tombak yang dipegang tentara bayaran.
“Atas nama ketertiban dan kemajuan,” kata Crawfurd, “Tuan kini resmi menjadi Sultan Ngayogyakarta.”
Sultan Raja mengangguk kecil. Wajahnya tenang, nyaris beku, seolah ingin menyembunyikan segala arus yang mengaduk di dalam dadanya. Ia bukan tak tahu bahwa dirinya dianggap durhaka. Tapi ia juga sadar, dalam belantara kekuasaan, kecepatan membaca arah angin bisa jadi lebih penting daripada kesetiaan darah.
Di kejauhan, para sentana kraton yang selamat dari pembantaian hari sebelumnya tak mampu menyembunyikan wajah getir mereka. Para abdi dalem, yang masih hidup, hanya tunduk dalam diam. Beberapa memilih tidak datang, lebih memilih menyembunyikan kesetiaan mereka pada Sultan Sepuh di balik anyaman tikar dan kelambu penderitaan.
Namun roda sejarah terus bergulir. Tak lama setelah penobatan itu, Sri Sultan Hamengku Buwana II dibuang ke Penang. Raffles, dengan wajah tenang dan nada bijak, menyebutnya sebagai langkah preventif. Tapi semua orang tahu, itu adalah penyingkiran.
Pangeran Notokusumo, saudara Sultan Sepuh, yang sejak awal menjalin komunikasi rahasia dengan Inggris, secara resmi diangkat menjadi adipati dari Kadipaten baru: Pakualaman. Raffles membaginya seperti membagi tanah jajahan. Kadipaten ini, katanya, akan menjadi mitra strategis Kesultanan agar Jogja tak lagi memberontak.
“Jogja harus dibelah agar tak bisa berdiri melawan,” ujar Crawfurd kepada asistennya, tanpa tahu bahwa kalimatnya kelak abadi sebagai luka sejarah.
Di rumah Notokusumo, perayaan kecil diselenggarakan. Para bangsawan kecil, yang sejak awal kecewa pada Sultan Sepuh, mulai merapat ke pihak yang baru. Mereka mengirim bingkisan, menyusun pujian, bahkan menulis serat-serat wangsalan yang memuji kebijakan baru dari Inggris. Namun di antara para puji itu, terselip rasa cemas: apakah mereka benar-benar telah memilih sisi yang tepat?
Pangeran Mangkudiningrat, anak kandung Sultan Sepuh dari permaisuri utama, kini bersembunyi bersama sisa laskar setia di wilayah timur, dekat Imogiri. Mereka menghindar dari pembantaian, menyimpan dendam yang mendidih dalam diam.
“Anak yang sah tak lagi punya tempat,” ucap Mangkudiningrat kepada seorang punakawan. “Yang menang bukan karena hak, tapi karena siapa yang berdiri di balik bayonet.”
Sementara itu, rakyat di luar benteng mulai menggambarkan peristiwa itu dengan getir. Kisah-kisah tentang prajurit Sepehi yang menjarah rumah-rumah, tentang perempuan keraton yang dipermalukan, dan tentang pusaka-pusaka kraton yang dibawa ke kapal Inggris di pelabuhan Semarang menjadi cerita bisik-bisik yang menyebar cepat.
Di tengah keruntuhan itu, seorang pujangga tua dari Kraton, Ki Yasadipura, mencatat dalam serat pribadinya:
“Sawijining rat pawewekan pepati,
tan oleh linangkung sudra ratu punika,
amukti garba tanpa wibawa,
anindakna dhuwur kawula.”
(Suatu raja yang memegang kekuasaan karena kematian,
bukan karena keluhuran,
memerintah tanpa wibawa,
dan memperlakukan rakyatnya seperti budak.)
Serat itu tak pernah dibacakan secara terbuka, tapi naskahnya tersimpan di bawah bale bambu, diwariskan secara diam-diam sebagai bentuk perlawanan halus.
Sementara Hamengku Buwana III mulai membentuk lingkar kekuasaannya, bayang-bayang pengkhianatan justru semakin tebal. Di istana, para pejabat baru mulai saling curiga. Masing-masing membawa kepentingan. Para penasihat Inggris mencatat semua gerak-gerik, memetakan siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang diam-diam masih loyal pada Sultan Sepuh.
Paku Alam I, alias Notokusumo, mulai sadar bahwa kekuasaannya adalah pisau bermata dua. Ia mendapat tanah dan pengaruh, tapi juga menjadi alat bagi penjajah untuk memecah tanah kelahirannya. Kadang, ia termenung di pendapa, menatap gamelan yang tak lagi berbunyi seperti dulu. Di antara segala kebesaran baru itu, ada sesuatu yang hilang—kepercayaan dari rakyatnya.
“Apakah aku pemenang,” gumamnya, “atau hanya pion yang akan segera disingkirkan ketika waktunya tiba?”
Di tengah pertanyaan itu, kabar datang dari pesisir selatan. Laskar-laskar kecil mulai berkumpul. Mereka menyebut diri mereka Prajurit Mangku Tanah. Mereka bersumpah akan mengembalikan hak waris Mangkudiningrat dan membalas segala penghinaan atas keraton.
Di bawah bayangan malam, perlawanan belum mati. (*)
(Bersambung seri ke-3: Api Dalam Sekam di Timur Imogiri)