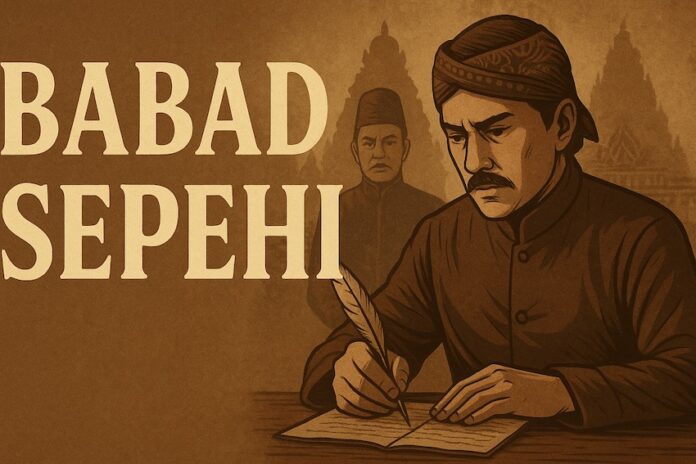BAYANGAN gunung dan kabut yang melingkupi kaki Imogiri tak mampu menutupi bara yang perlahan membesar di tengah diam. Di sisi timur kompleks makam raja-raja Mataram itu, di antara kebun salak dan hutan jati yang mengering, berkumpul sekelompok laki-laki bersarung lusuh dan bersenjata seadanya. Mereka bukan bangsawan, bukan pula prajurit resmi, namun setiap dari mereka memendam luka yang sama: marah atas penghinaan terhadap kraton, dan pada sistem yang telah membuang kehormatan warisan Mataram hanya demi persekutuan dengan bangsa asing.
Pangeran Mangkudiningrat berdiri di hadapan mereka, tak bersorban, hanya mengenakan ikat kepala dan baju lurik kelam. Ia bicara dengan suara dalam, tak menggebu, namun setiap katanya menghunjam hati pendengarnya.
“Kita bukan pemberontak. Kita adalah waris sah dari darah yang diludahi. Jangan berharap bantuan dari keraton, karena keraton kini telah menjadi papan catur. Jangan berharap belas kasihan Inggris, karena mereka hanya mengerti emas dan kekuasaan. Kita adalah sisa dari Mataram yang belum dibeli dan belum menyerah.”
Para lelaki itu, kebanyakan bekas prajurit yang tercerai, petani yang tanahnya dijarah Sepehi, dan bahkan beberapa anak muda yang baru belajar memegang keris, menjawab dengan pekik lirih: “Inggih, Sinuwun…”
Gerakan itu tak menamakan dirinya secara resmi. Mereka hanya saling menyapa sebagai sedulur satunggaling rasa. Tapi orang-orang luar mulai menyebut mereka sebagai “Api Imogiri” – gerakan bawah tanah yang menyelinap dari desa ke desa, menyebar semangat perlawanan terhadap Inggris dan keraton baru.
Kabar keberadaan mereka membuat Raffles gusar. Ia menganggap bahwa pengasingan Sultan Sepuh dan pengangkatan Sultan Raja telah meredakan ketegangan. Namun laporan dari Crawfurd dan mata-mata lokal menunjukkan bahwa gerakan di selatan tak bisa diremehkan. Bahkan beberapa desa di Bantul dan Pajangan mulai menolak membayar pajak pada otoritas Inggris.
Raffles memerintahkan residen-residen pribumi yang baru diangkat, termasuk di dalamnya Bupati Danureja, untuk memetakan siapa saja yang dianggap berpotensi menghasut rakyat. Namun langkah itu justru menimbulkan efek sebaliknya. Penduduk desa, yang semula diam, mulai menunjukkan resistensi pasif—tidak menyambut pejabat, menolak bicara bahasa Melayu, dan kembali menggelar ritual sedekah bumi sebagai simbol penolakan atas kekuasaan asing.
Di sebuah rumah panggung yang tersembunyi di balik semak lebat, para tokoh gerakan bawah tanah berkumpul. Ada Ki Bekel dari Guwosari, mantan cantrik dari Padepokan Suroloyo, seorang juru tulis dari Banyusumurup, dan bahkan seorang bekas punggawa kraton yang kehilangan saudara perempuannya saat benteng dijarah Sepehi.
“Kita tidak butuh perang terbuka,” ujar Ki Bekel, “kita tanam semangat ini seperti bibit cabai. Biarkan ia tumbuh di hati rakyat. Biarkan rakyat sendiri yang kelak menolak kekuasaan yang tak punya sah.”
Mangkudiningrat mengangguk. Ia sadar bahwa kekuatan mereka tak cukup untuk merebut kembali tahta. Tapi ia juga tahu, bahwa sejarah bukan hanya ditulis oleh pemenang, melainkan oleh mereka yang terus mengingat luka.
Sementara itu, di Kraton, Sultan Raja mulai dilanda keraguan. Gelar dan tahta memang telah digenggam, tetapi pengaruhnya belum meresap. Para abdi dalem tampak enggan patuh sepenuh hati. Bahkan para sinden gamelan enggan menyanyikan lagu-lagu pujian yang biasa dipersembahkan untuk raja. Beberapa pujangga diam-diam berhenti menulis tembang, memilih bertani atau meninggalkan keraton.
Dalam sebuah pertemuan terbatas, Raffles menegur para pejabat pribumi.
“Kekuasaan bukan soal pedang dan surat pengangkatan. Ini soal legitimasi. Jika rakyat masih memuja raja yang dibuang, maka segala struktur yang kalian bangun akan runtuh seperti pasir.”
Perkataan itu menusuk. Tapi tak ada yang mampu menjawab.
Di Imogiri, sepasang bocah duduk di bawah cungkup makam Sultan Agung. Mereka membawa kemenyan dan bunga. Di tengah kabut pagi yang tebal, si sulung berkata lirih, “Apa Mataram akan kembali jaya, Kakang?”
Sang kakak tersenyum kecil, menatap ukiran aksara Jawa di batu nisan, lalu menjawab, “Jika kita tidak lupa pada namanya, dan tak tunduk pada mereka yang menjajah dengan seragam kemegahan, maka iya… Mataram akan kembali, meski hanya sebagai semangat.”
Di kejauhan, asap tipis dari dapur-dapur gerilya masih mengepul. Api belum padam. Hanya menunggu waktu untuk menyala lebih besar.
(Bersambung seri ke-4: Dalang-dalang Bayangan dari Baluwarti)