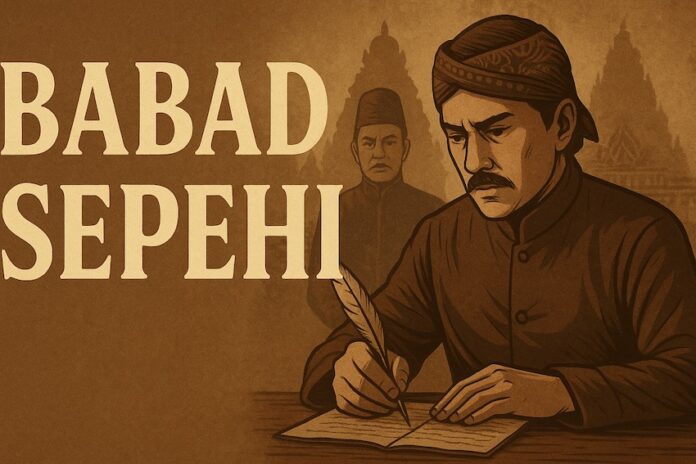JAYENGRATNA duduk di bawah lampu minyak yang berkedip. Tangannya gemetar, tapi bukan karena usia. Dalam jiwanya, badai mengamuk. Ia bukan prajurit. Ia bukan dalang. Tapi ia penulis yang tahu bahwa kata-kata bisa lebih tajam dari keris yang terhunus.
Malam itu ia menyelesaikan sebagian dari serat rahasia, sebuah lontar yang ia susun dengan kehati-hatian setara menyulam angin. Lontar itu bukan tembang pujian seperti yang biasa ia tulis untuk para penguasa. Bukan pula cerita wayang yang memuja para dewa. Melainkan kesaksian yang ia beri judul: “Babad Sepehi – Tanggapan Sang Pujangga atas Kehancuran Tahta dan Martabat.”
Ia tahu betul bahwa jika lontar itu jatuh ke tangan orang yang salah, hidupnya akan dicabut diam-diam seperti bunga layu yang dicopot dari jambangan. Tapi Jayengratna bukan sekadar ingin hidup. Ia ingin generasi sesudahnya tahu: bahwa ada yang tidak beres, dan ada yang melawan meski dengan pena.
Lontar itu tidak pernah selesai sepenuhnya. Bukan karena Jayengratna kekurangan kata, tapi karena malam-malam di Yogya semakin tak menentu. Patroli Sepehi kini merambah hingga ke lorong-lorong kecil di Kotagede. Kabarnya, Tumenggung Wangsasaputra menyebar daftar “penulis subversif” kepada aparat kawedanan. Dan nama Jayengratna ada di urutan keempat.
Suatu malam, Jayengratna merasa waktu tak lagi berpihak. Ia menyerahkan lontar yang belum rampung itu kepada Sindhu, si penjual tembakau yang ternyata anggota jejaring rahasia Mangkudiningrat.
“Bawalah ini ke Imogiri,” katanya lirih. “Jika aku tidak sempat menyelesaikannya, biarlah anak-anak dusun yang meneruskannya dengan lidah mereka. Cerita tak butuh tinta untuk hidup.”
Sindhu menerima dengan penuh hormat. Ia tahu betapa mahal dan rapuhnya lembar-lembar itu. Ia sembunyikan lontar tersebut dalam gulungan tembakau kering, lalu berangkat menyusuri jalur tikus yang biasa ia tempuh menuju selatan.
Namun, malam itu pula Jayengratna tidak kembali ke rumahnya. Di pendopo tempat ia biasa duduk melantunkan tembang, hanya ditemukan cangkir teh yang belum sempat kosong dan buku kosong di atas meja. Desas-desus menyebutkan bahwa ia ditangkap, dibawa diam-diam, lalu dihilangkan. Tapi tidak ada catatan resmi. Tidak ada pusara. Seperti tembangnya, ia menghilang dalam bait tak bersuara.
Sementara itu di Imogiri, Mangkudiningrat menerima lontar Jayengratna dengan mata berkaca-kaca. Ia membacanya dengan perlahan, setiap baris diserap dalam hati. Di bawah sinar lentera, ia bersumpah:
“Jika pena ini tak sempat selesai menuliskan babad, maka kita akan menuliskannya dengan langkah kaki dan nyawa.”
Lontar itu kemudian disalin oleh para santri di pesantren-pesantren pegunungan. Dibaca dalam pengajian tertutup. Diubah menjadi tembang sindiran dan dimainkan dalam pertunjukan wayang keliling. Nama Jayengratna mulai disebut dengan bisik bangga di dusun-dusun yang menyimpan bara perlawanan.
Sementara di Baluwarti, Tumenggung Wangsasaputra mulai mencium bahwa ada gelombang bawah tanah yang tak terbendung. Para pengintai melaporkan bahwa tembang-tembang aneh mulai dinyanyikan anak-anak di pasar:
“Sultan duduk di kursi perak,
bayang-bayangnya bukan bayang leluhur,
tangannya menggenggam jam asing,
tapi waktunya tak ia kenali.”
Bagi Tumenggung, tembang itu adalah tanda bahaya. Ia pun memerintahkan penggeledahan lebih ketat, melarang pertunjukan wayang keliling tanpa izin, bahkan menyarankan Sultan untuk membuat versi resmi sejarah Serangan Sepehi yang menyingkirkan para saksi bawah tanah.
Namun sejarah tak bisa dibungkam selamanya.
Pada malam Jumat Kliwon di Gunung Kidul, seorang santri membaca bagian terakhir lontar Jayengratna yang sempat tertulis:
“Jika tahta dibangun di atas debu pengkhianatan, maka angin sejarah akan meniupnya perlahan. Pelan-pelan. Tapi pasti. Seperti abu duka yang mencari jalan pulang.”
Dan di saat yang sama, di bawah bayang pohon sawo tua dekat pemandian Taman Sari, seseorang menyusun kembali potongan babad yang hilang. Sejarah yang dicuri sedang ditulis ulang. Bukan di istana. Tapi di hati rakyat yang belum menyerah.
(Bersambung seri ke-6: Pasamuan Rahasia di Watu Gilang)