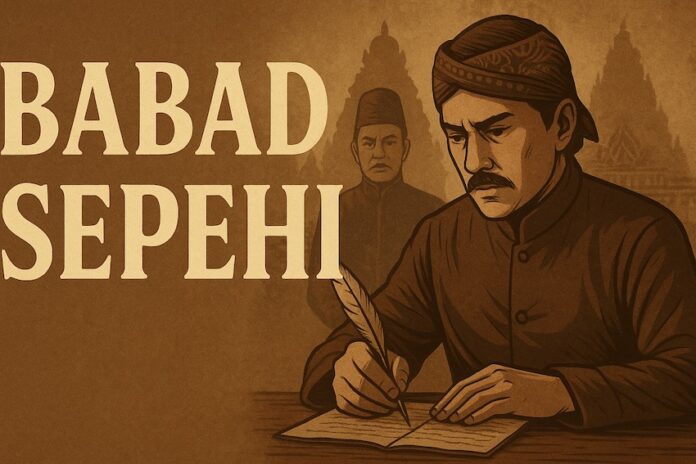ANGIN dari arah selatan membawa bau anyir pagi hari yang mencurigakan. Di balik tembok keraton, tepatnya di ruang tamu kecil dekat pendapa Manguntur Tangkil, suasana terasa lebih dingin daripada biasanya. Sultan HB II duduk dengan raut yang sukar dibaca, hanya sesekali menggerakkan jari-jarinya yang menggenggam sabuk emas pusaka.
Yang hadir pagi itu bukan sembarang orang. Tumenggung Wangsasaputra, Adipati Anom, dan Patih Danurejo IV duduk di seberang sang Sultan, masing-masing menyembunyikan gundah dan ambisi mereka dalam diam. Di sisi ruangan, Kapten Collins—utusan Raffles—berdiri tegak sambil memperhatikan perdebatan internal itu dengan pandangan waspada.
“Kauman semakin berani,” ujar Danurejo, suaranya tenang tapi beracun. “Ada jaringan rahasia yang memantau kita dari dalam. Hamba menduga mereka menyusup lewat abdi dalem dan pedagang pasar.”
Wangsasaputra menimpali, “Tapi kekerasan terhadap Kauman bisa membakar kota. Mereka bukan sekadar kampung, tapi jantung kepercayaan rakyat.”
Kapten Collins menyela, “Her Majesty’s interest is in stability. Kami ingin Yogyakarta tetap tenang. Namun jika keraton tak mampu mengatur rumahnya sendiri… maka pasukan Sepehi bisa mengambil alih.”
Ucapan itu seperti sembilu. HB II menghela napas panjang, lalu menatap dinding bertuliskan ayat-ayat suci yang mulai memudar. Di dalam hatinya, ia tahu: kuasa kini bukan di tangannya, tapi di tangan mereka yang bersenjata dan pandai memanipulasi janji.
Sementara di lorong-lorong belakang keraton, sekelompok abdi dalem senior diam-diam menggelar pasamuan rahasia. Ki Jayeng Wiratma, juru kunci Sasana Sekar, memimpin rapat kecil itu. “Kita tidak bisa berharap pada Sultan yang gamang. Tapi kita juga tak boleh membiarkan Inggris dan Danurejo mengoyak martabat tanah ini,” ucapnya dengan tenang.
Beberapa di antara mereka pernah menjadi penghubung dengan gerakan bawah tanah. Salah satunya, abdi muda bernama Mertopuro, yang dulunya murid dari Kanjeng Lintang, kini bekerja sebagai pengantar pusaka di dalam keraton. Melalui jalur tersembunyi di balik tembok keraton, ia menyampaikan pesan ke luar: peta pergerakan pasukan Sepehi, rencana razia, hingga siapa saja pejabat keraton yang mulai menjual tanah dan pengaruh kepada Inggris.
Intrik di balik tembok keraton tak hanya soal politik, tapi juga pertarungan kepercayaan. Sebagian bangsawan mulai memeluk ide “modernisasi” ala Inggris, berharap diberi tanah dan jabatan. Tapi sebagian lainnya tetap teguh memegang adat dan sabda leluhur. Mereka melihat Inggris bukan penyelamat, melainkan penjajah licik yang menyamar sebagai pedagang.
Di sudut bangsal kesenian, seorang sinden keraton bernama Ratmi menyusun tembang baru: semacam kidung sindiran yang jika dinyanyikan pelan, bisa menjadi kode untuk jaringan luar. Ratmi dulunya anak dari pengungsi Tegalrejo yang rumahnya dibakar pasukan Sepehi. Kini ia menyamar sebagai penghibur dalam pesta-pesta dansa para petinggi Inggris. Dalam setiap tarian dan senyumnya, ada amarah yang ditahan.
Suatu malam, Sultan HB II memanggil Ratmi secara khusus. “Aku tahu kau bukan sekadar penari,” ujarnya lirih.
Ratmi menunduk. “Saya hanya menjalankan peran, Kanjeng Sultan.”
HB II menatap mata Ratmi. Di sana ia melihat keteguhan yang telah lama hilang dari wajah bangsawannya sendiri. “Jika kelak sejarah ditulis ulang,” ucap Sultan pelan, “semoga engkau masih menari, tapi bukan untuk menghibur penjajah, melainkan untuk merayakan kemerdekaan yang sejati.”
Ucapan itu menggantung, seperti doa yang tertunda. Sebab jauh di dalam hati HB II, ada sesuatu yang bergolak. Ia ingin lepas dari belenggu Inggris, tapi tak punya keberanian seperti ayahandanya, atau tekad seperti rakyat yang kini bergerilya dalam diam.
Sementara itu, Danurejo IV mengirim utusan khusus ke Batavia. Ia tahu bahwa kesempatan emas sedang datang. Jika HB II terlihat tak mampu menjaga stabilitas, maka gelar Sultan bisa saja diganti. Ia, Danurejo, tengah merancang kemungkinan itu: menjadi regent, bahkan mungkin penguasa boneka yang sepenuhnya di bawah Inggris.
Intrik demi intrik itu menjalar bagai akar beringin, menyusupi setiap sudut keraton. Tapi akar lain juga tumbuh di luar: rakyat, ulama, sinden, abdi dalem, dan para pemuda diam-diam menyusun perlawanan yang tak bisa dibaca di meja-meja rapat para penguasa.
Ketika malam kembali menyelimuti Jogja, langit tampak lebih gelap. Tapi justru dalam kegelapan itulah, panah-panah rahasia mulai dilepaskan dari Kauman, pesan diselundupkan dari dalam keraton, dan sejarah diam-diam sedang disusun ulang, satu persatu.
(Bersambung seri ke-9: Kabar dari Watu Gilang)