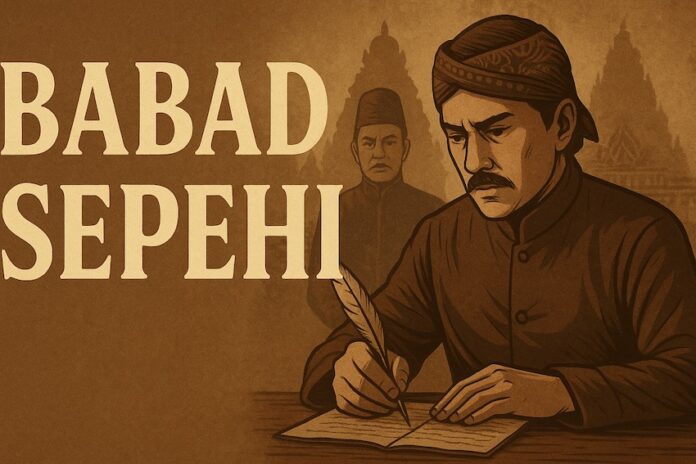WATU Gilang tak pernah setenar Tamansari atau Gedhong Kuning, tapi para pemuda yang berani bersumpah dengan darah tahu: batu itu adalah saksi abadi. Dulu, konon, batu itu dipakai sebagai alas penobatan raja. Kini, ia menjadi tempat pengucapan ikrar perlawanan dalam bisu.
Malam itu, bulan nyaris bundar. Bayangan pepohonan menari di sela kabut tipis. Di balik rerimbun bambu, sepuluh orang berkumpul dalam lingkaran. Mereka bukan bangsawan. Tak ada jubah halus atau keris berhulu emas. Tapi di mata mereka, menyala sesuatu yang jauh lebih berharga: kemarahan dan keyakinan.
Mangkudiningrat memimpin pasamuan. Di sisi kanannya, Sindhu si kurir tembakau duduk bersila. Di kirinya, seorang abdi dalam bernama Reksapraja yang telah membelot secara diam-diam sejak melihat kawan-kawannya dihina dan dipecat oleh para Sepehi.
“Apa kalian sudah siap dengan sumpah?” suara Mangkudiningrat pelan, tapi tegas.
Reksapraja menjawab pertama, “Selama darahku mengalir, tak akan ada pengkhianat yang duduk nyaman di singgasana Jogja.”
Disusul suara-suara lain, satu per satu. Ada pembuat gamelan dari Pleret. Ada guru surau dari Gunung Kidul. Bahkan seorang perempuan dari kampung Kauman, Kanjeng Lintang, yang diam-diam melatih para gadis memanah dengan alasan belajar tari. Semua telah melihat cukup banyak penghinaan.
Lalu, Mangkudiningrat mengeluarkan secarik kain putih. Di atasnya, ia menulis dengan tinta hitam:
“Prasetya Watu Gilang: Kami, rakyat yang terinjak, bersumpah menuliskan kembali sejarah dengan darah kami jika pena tak lagi diizinkan menari.”
Mereka menandatangani dengan sidik jari. Mangkudiningrat menutup ritual itu dengan membaca bait terakhir dari lontar Jayengratna. Tangannya sedikit bergetar.
“Batu ini tidak bicara, tapi ia mencatat,” gumamnya, lalu mengubur kain bertulis sumpah itu di bawah Watu Gilang.
Tak jauh dari sana, pasukan Tumenggung Wangsasaputra mulai menyebar. Seorang mata-mata mereka mencium gerakan mencurigakan. Namun informasi itu terlambat. Saat mereka tiba, tempat itu sudah sepi. Tapi mereka menemukan secarik daun lontar terselip di sela batu.
Tertulis:
“Kami mungkin tiada,
tapi sejarah tak tidur.
Batu merekam,
dan anak-anakmu akan bertanya
kenapa malam lebih jujur dari istana.”
Kabar tentang pasamuan Watu Gilang berembus cepat. Meski dirahasiakan, tembang tentang “Sumpah Watu Gilang” mulai diperdengarkan di surau dan warung kopi. Lantunannya lirih tapi menggetarkan. Sultan HB II yang mulai resah meminta agar Tumenggung menindak siapa saja yang menyanyikan tembang itu.
“Ini bukan pemberontakan bersenjata, Gusti,” ujar Tumenggung dalam sinisnya. “Ini pemberontakan cerita. Lebih berbahaya.”
Sementara itu, Gubernur Raffles di Semarang mendengar laporan intelijennya sendiri. Ia menilai kisruh di Jogja bukan hanya urusan takhta, tapi soal kelangsungan citra Inggris di Jawa. Maka ia mengirim utusan bernama Letnan Foster, seorang pendiam berkaca mata bulat, untuk menyusup sebagai pengajar bahasa di lingkungan pesantren. Foster diam-diam mencatat siapa bicara apa.
Namun Foster tak tahu, di balik keramahan para santri, mereka justru mempelajari bagaimana cara membaca peta kolonial dan menyampaikan kabar antar dusun lewat sandi tembang. Sementara itu, nama Jayengratna mulai disebut-sebut seperti legenda.
“Batu itu pernah jadi alas raja,” ujar seorang santri. “Kini, jadi penopang sumpah kami.”
Di masa itu, sejarah memang tidak hanya ditulis oleh para penakluk. Tapi juga oleh mereka yang diam-diam mengutuk dalam syair, menyalakan lentera dalam gelap, dan menulis babad bukan demi kejayaan, melainkan demi kejujuran. Dan dari Watu Gilang, bara itu mulai menyala.
(Bersambung seri ke-7: Kanjeng Lintang dan Panah dari Kauman)